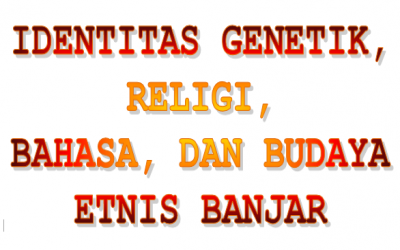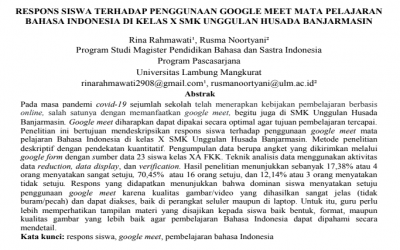Oleh :
ERMA NOORMAWATI, S. Pd
Secara genetik etnis Banjar adalah orang Dayak (Balangan, Bakumpai, Barito, Dusun, Halong, Maanyan, Lawangan, Maratus, Ngaju, Ot Danum, Siang, dan suku bangsa lainnya), yang memilih agama Islam sebagai agama anutannya.
Para raja yang berkuasa di Kerajaan Nan Sarunai, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, dan Kerajaan Banjar, semuanya berdarah Maanyan. Demi memperkokoh identitasnya sebagai kolektif suku bangsa yang baru, maka selain dilekati dengan identitas genetika (orang Dayak) dan identitas religi (penganut agama Islam), orang Banjar juga mulai dilekati dengan 2 identitas lain, yakni identitas bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan (lingua franca), dan identitas budaya sungai.
Identitas Genetik
Identitas religi sebagai penganut agama Islam yang saleh mulai dilekatkan sebagai identitas baru kepada penduduk asli Pulau Kalimantan sejak tahun 1526, yakni sejak Sultan Suriansyah memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Banjar yang berideologi ajaran agama Islam.Konsekwensi logis akibat ditetapkannya ajaran agama Islam sebagai ideologi negara adalah ditempatkannya agama Islam sebagai agama resmi di Kerajaan Banjar.Politik religius ini sudah barang tentu akan menempatkan warga negara Kerajaan Banjar yang beragama Islam sebagai warga negara kelas satu.
Tertarik dengan ajaran agama Islam yang begitu istimewa berikut status sosial politik yang juga istimewa, maka semakin hari semakin banyak saja warga negara Kerajaan Banjar yang melepaskan keyakinan lamanya untuk kemudian memeluk agam Islam.
Penetapan agama Islam sebagai agama resmi atau ideologi negara di Kerajaan Banjar bukannya tanpa masalah, warga negara Kerajaan Banjar yang beragama Hindu, Budha, Kaharingan, dan penganut agama yang lainnya memilih pindah menjauhi pusat pemerintahan.
Warga negara Kerajaan Banjar yang tidak memeluk agama Islam inilah yang di kemudian hari menjadi cikal bakal suku bangsa Balangan, Barito, Dusun, Lawangan, Maratus, Halong, Ngaju, Ot Danum, Siang, dan suku bangsa lainnya.
Pada tahun 1895, Dr. August Kaderland memperkenalkan istilah etnis Dayak untuk menyebut semua kolektif suku bangsa penduduk asli Pulau Kalimantan yang belum memeluk agama Islam.
Pasca runtuhnya Kerajaan Banjar pada tahun 1905, istilah orang Banjar tidak lagi dipahami sebagai istilah kesatuan politik (warga negara Kerajaan Banjar), tetapi sudah mengalami pengerucutan sebagai istilah kesatuan suku bangsa (etnis Banjar).
Identitas Religi
Agama merupakan penanda identitas yang bersifat situasional yang dengan sadar dapat dilekatkan pada suatu kolektif suku bangsa tertentu, baik oleh suku bangsa itu sendiri, maupun oleh suku bangsa lainnya. Pada kasus-kasus tertentu, seseorang atau sekelompok orang yang pindah agama tidak saja berakibat pada terjadinya perubahan dalam hal identitas agamanya, tetapi juga dapat berakibat pada terjadinya perubahan dalam hal identitas suku bangsanya.
Perubahan identitas suku bangsa dimaksud terjadi pada kasus masuk Islamnya suku bangsa Balangan, Barito, Dusun, Lawangan, Maanyan, Maratus, Halong, Ngaju, Ot Danum, dan Siang sejak tahun 1526. Begitu yang bersangkutan pindah keyakinan menjadi pemeluk agama Islam maka identitas suku bangsanya secara praktis akan berubah menjadi orang Banjar.
Orang Dayak yang memeluk agama Islam akan dikatakan sebagai telah menjadi orang Banjar. Ini berarti, secara genetik orang Banjar adalah orang Dayak yang memeluk agama Islam. Orang Dayak yang memeluk agama Islam disebut Hakey. Orang Maanyan yang memeluk agama Islam disebut Matanu atau Mangantis.
Pada zaman Kerajaan Banjar (1524-1905) dahulu, orang-orang Dayak yang memeluk agama Kaharingan atau memeluk agama Kristen akan tetap menyebut diri mereka sebagai orang Dayak. Sedangkan orang Dayak yang memeluk agama Islam menyebut diri mereka orang Banjar. Pengecualian terjadi pada suku Bakumpai, Baraki, dan Barangas, yang meskipun sudah memeluk agama Islam dan mempergunakan bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulannya, namun mereka tidak disebut orang Banjar, tetapi tetap disebut orang Bakumpai, Baraki, dan Barangas. Orang Dayak Pagan dan orang Dayak Taman (Dayak Ma-loh) akan dianggap sebagai orang Melayu jika yang bersang-kutan memeluk agama Islam.
Kebanyakan orang Dayak di Kaltim dikaitkan dengan agama Kristen, yakni agama yang dalam kasus ini saling dipertentangkan dengan agama Islam sebagai agama yang dominan di Indonesia. Bila seorang Dayak masuk Islam, mereka tidak lagi dianggap sebagai orang Dayak, tetapi justru menjadi orang Melayu. Proses pergeseran identitas etnisitas semacam ini juga ditemukan faktanya oleh Winzeler. Dengan nada serupa Winzeler menengarai orang Dayak Bidayuh yang menjadi muslim tidak lagi diakui oleh suku bangsanya sebagai orang Dayak Bidayuh. Memang, pada tempat-tempat tertentu di Pulau Kalimantan, orang Dayak tidak dengan sendirinya berbeda jauh dari kelompok-kelompok suku bangsa di sekitarnya.
Sehubungan dengan kasus-kasus semacam itu sangatlah problematis jika harus menunjukan batasan yang saling membedakan antara orang Dayak di satu pihak dengan orang Melayu di pihak lain.
Kebertumpang-tindihan budaya semacam ini barangkali sudah menjadi aturan ketimbang perkecualian. Faktor kesamaan wilayah dapat membuat semua kebudayaan menjadi saling terkait, tidak ada yang tunggal dan murni, semuanya hybrid, heterogen, tidak monolitik, dan tidak ada yang luar biasa. Kelompok Dayak yang menggunakan bahasa Banjar, beragama Islam dan saling bercampur darah karena kawin mawin dengan suku Melayu dan Jawa, lambat laun akan berubah identitas etnisnya menjadi orang Banjar.
Identitas Bahasa
Menurut hasil penelitian Wurm dan Willson (1975), hubungan kekerabatan (kognat) antara bahasa Banjar dengan bahasa Melayu menyentuh angka 85 persen.
Tapi, ini bukan berarti bahasa Melayu yang mempengaruhi bahasa Banjar, sebaliknya bahasa Banjar yang justru mempengaruhi bahasa Melayu. Banyak di antara kosa-kata bahasa Melayu itu yang berasal atau berakar dari bahasa Banjar, bukan sebaliknya.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa suku bangsa Melayu tidak pernah mendominasi kehidupan sosial politik dan sosial budaya di wilayah tempat tinggal purba etnis Banjar (di zaman Kerajaan Nan Sarunai, Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, dan Kerajaan Banjar).
Ketika suku bangsa Melayu warga negara Kerajaan Sriwijaya melakukan migrasi pada tahun 1025-1026, Kerajaan Nan Sarunai sudah menjadi negara yang mapan secara sosial politik dan sosial budaya. Begitu pula halnya yang terjadi ketika suku bangsa Melayu warga negara Kerajaan Melaka melakukan migrasi pada tahun 1511, Kerajaan Negara Daha sudah menjadi negara yang mapan secara sosial politik dan sosial budaya. Sehingga bagaimana mungkin suku bangsa Melayu sebagai suku bangsa pendatang yang jumlahnya tidak begitu signifikan dapat melakukan penetrasi sosial budaya yang begitu telak ke jantung peradaban warga negara Kerajaan Nan Sarunai (1025-1026) atau Kerajaan Negara Daha (1511).
Bahasa yang mereka pergunakan sebagai bahasa pergaulan (liungua franca) juga berasal dari bahasa yang bersifat semula jadi yang diwarisi oleh nenek moyang mereka ketika masih tinggal di Yunan dahulu.
Teori lain yang juga relevan adalah teori Blust (1988), dan Adelaar (1992). Keduanya menolak hipotesis bahwa asal-usul orang Melayu adalah di Semenanjung Melayu (Malaysia dan Kepulauan Riau). Merujuk pada keyakinan Blust dan Adelaar, maka itu berarti bahasa Melayu purba juga tidak berasal dari Semenanjung Melayu sebagaimana yang dulu pernah diyakini oleh para ahli bahasa. Melalui pendekatan keaneka-ragaman bahasa tertinggi (maximun diversity), Collins (1975), dan Notherper (1996) berpendapat bahwa asal-usul bahasa Melayu adalah di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalbar. Bahasa Melayu purba merupakan bahasa yang terbentuk dari hasil kompilasi bahasa-bahasa yang ada di Pulau Kalimantan, seperti bahasa Banjar, Berau, Iban, Sambas, Sarawak, Ketapang, dan Kutai. Selain berkognat dengan bahasa Melayu, bahasa Banjar juga berkognat dengan sejumlah bahasa lain di Kalsel dan Kalteng. Menurut Zaini HD (2000:4), bahasa Banjar berkognat dengan bahasa Maanyan (32 %), dan dengan bahasa Ngaju (39 %).
Fakta ini semakin mengukuhkan premis atau hipotesis bahwa etnis Banjar di Kalsel sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan secara sosial genetika dan sosial budaya dengan suku bangsa Dayak Maanyan, Dayak Ngaju, dan lebih-lebih lagi dengan Dayak Meratus.
Bahasa Dayak Bukit (saudara kita ini lebih senang disapa Dayak Maratus, pen) tidak lain adalah bahasa Banjar yang agak kuno. Bahasa Bukit merupakan salah satu subdialek Bahasa Banjar Hulu. Bahasa Bukit lebih dekat hubungannya dengan Bahasa Banjar Hulu sehingga dapat saja disebut atau dianggap sebagai Bahasa Banjar purba (arkais).
Asal-usul nenek-moyang orang Banjar sama dengan etnis Dayak pada umumnya, yakni ras Melayu Malayan Mongoloid yang berasal dari Propinsi Yunan di Republik Rakyat Cina sekarang ini. Bukan ras Melayu yang berasal dari Semenanjung Melayu, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Selain itu, dalam khasanah cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Maratus juga ditemukan legenda yang sifatnya mengakui atau bahkan melegalkan keserumpunan genetika (saling berkerabat secara geneologis) antara orang Banjar dengan orang Dayak Maratus. Dalam cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus dimaksud terungkap bahwa nenek moyang orang Banjar yang bernama Bambang Basiwara adalah adik dari nenek moyang orang Dayak Maratus yang bernama Sandayuhan. Bambang Basiwara digambarkan sebagai adik yang berfisik lemah tapi berotak cerdas. Sedangkan Sandayuhan digambarkan sebagai kakak yang berfisik kuat dan jago berkelahi. Sesuai dengan statusnya sebagai nenek-moyang atau cikal-bakal orang Dayak Maratus, maka nama Sandayuhan sangat populer di kalangan orang Dayak Maratus. Banyak sekali tempat-tempat di seantero pegunungan Meratus yang sejarah keberadaannya diceritakan berasal-usul dari aksi heroik Sandayuhan.
Identitas Budaya Sungai
Secara budaya, Idwar Saleh melekatkan identitas sebagai suku bangsa dengan kebudayaan berbasis sungai kepada etnis Banjar di Kalsel. Suku bangsa Banjar di Kalsel adalah hasil pembauran yang unik dari sejarah sungai-sungai Bahau, Barito, Martapura, dan Tabunio. Seluruh kehidupan manusia di daerah Kalsel, terutama suku Banjar, hampir 80%, sampai ke udik ditandai oleh suatu budaya yang khas, yang disebut kebudayaan sungai.
Atmojo dkk memaparkan bahwa sejak zaman purba hingga sampai saat ini sungai-sungai di Kalsel berfungsi sebagai tempat konsentrasi pemukiman penduduk dan menjadi prasarana lalu lintas yang menghubungkan daerah muara dengan pedalaman. Bagi etnis Banjar di Kalsel sungai adalah jantung kehidupan, karena kehidupan mereka sangat dekat dengan sungai. Antara masyarakat dengan sungainya saling berinteraksi, beradaptasi, dan saling isi mengisi. Bermula dari fakta inilah maka etnis Banjar di Kalsel dikenal luas sebagai suku bangsa yang identik dengan budaya sungai.
Kampung, bandar, dan keraton yang menjadi tempat konsentrasi pemukiman di Kalsel memang selalu di bangun di muara sungai atau di persimpangan sungai.
Selain menghasilkan air untuk minum, mandi, dan mengairi sawah pasang surut, sungai juga menjadi tempat yang ideal untuk ikan berkembang biak.
Kampung-kampung di Kalsel dibuat dengan cara memanjang di sepanjang sungai, ada rumah yang dibangun di atas rakit dan ada pula rumah yang dibangun di atas tebing.
Pada masa-masa yang telah lalu, di daerah-daerah seperti itulah penduduk di daerah setempat dan para pendatang dari luar daerah membangun pusat-pusat pemerintahan.
Kriteria tempat tinggal ideal bagi suku bangsa yang mengakrabi budaya sungai ketika itu adalah tempat yang berdekatan dengan teluk yang dalam dan berair tenang atau tempat berdekatan dengan sungai besar berair dalam. Tapi, teluk atau sungai dimaksud harus terletak di daerah pedalaman, dalam hal ini daerah pedalaman yang mampu memasok air tawar, bahan makanan, dan komoditi perdagangan yang sangat dibutuhkan konsumen di luar negeri, seperti : damar, emas, intan, karet, kayu gaharu, kayu gelondongan, lada, madu, pangan, papan, rotan, sarang burung walet dan lain-lain. Hubungan perdagangan dengan luar negeri inilah yang menjadi faktor utama tumbuh pesatnya kota-kota pedalaman di tepi sungai dan teluk dimaksud.